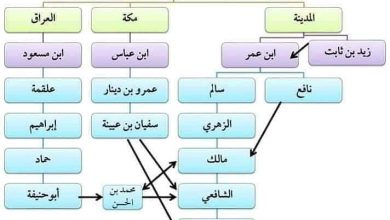Fiqih
Hadiah

Hadiah (hadiyyah) berasal dari kata hadâ wa ahdâ. Bentuk pluralnya hadâyâ atau hadâwâ menurut bahasa penduduk Madinah. Hadiah secara bahasa berarti sesuatu yang Anda berikan (mâ athafa bihi).1 Pengertian ini belum cukup karena tidak semua pemberian merupakan hadiah. Pemberian itu bisa berupa sedekah, wakaf, hibah, pinjaman ataupun wasiat.
Secara istilah, dalam al-Qâmûs al-Fiqhî dinyatakan, menurut ulama Syafiiyah, Hanabilah, Hanafiyah dan Malikiyah, hadiah adalah tamlîku ’ayn bi lâ ’iwadh ikrâm[an] ilâ al-muhdâ ilayh (pemindahan pemilikan suatu harta tanpa kompensasi sebagai penghormatan kepada orang yang diberi hadiah).2 Dalam Mu’jam Lughah al-Fukahâ’, hadiah adalah al-’athiyah bi lâ ’iwadh ikrâman (pemberian tanpa kompensasi sebagai suatu penghormatan). Hadiah juga bermakna i’thâ’ syay’[in] bighayr ‘iwadh shilat[an] wa taqarrub[an] wa ikrâm[an] (pemberian sesuatu tanpa kompensasi karena adanya hubungan, untuk menjalin kedekatan dan sebagai bentuk penghormatan).3
Yang jelas, hadiah merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Kalau yang diberikan adalah manfaatnya sementara zatnya tidak maka itu merupakan pinjaman (i’ârah). Karenanya hadiah haruslah merupakan tamlîkan li al-’ayn (pemindahan/penyerahan pemilikan atas suatu harta kepada pihak lain). Penyerahan pemilikan itu harus dilakukan semasa masih hidup karena jika sesudah mati maka merupakan wasiat. Di samping itu penyerahan pemilikan yang merupakan hadiah itu harus tanpa kompensasi (tamlîkan li al-’ayn bi lâ ’iwadh), karena jika dengan kompensasi maka bukan hadiah melainkan jual-beli (al-bay’).
Pengertian itu belum spesifik menunjuk hadiah. Menurut para ulama, tamlîkan li al-’ayn itsnâ’ al-hayah bi lâ ’iwadh ini merupakan hibah, sementara hibah itu mencakup tiga macam: hibah dalam arti khusus, sedekah dan hadiah. Imam an-Nawawi mengatakan:4
Imam Syafii membagi tabarru‘ât (pemberian) seseorang kepada yang lain menjadi dua bagian: yang dikaitkan dengan kematian dan itu adalah wasiat; yang dilakukan saat masih hidup. Pemberian saat masih hidup ini ada dua bentuk: murni pemindahan pemilikan seperti hibah, sedekah dan wakaf. Yang murni pemindahan pemilikan itu ada tiga macam: hibah, sedekah sunah dan hadiah. Jalan untuk menentukannya adalah kita katakan pemindahan pemilikan tanpa kompensasi (tamlîk bi lâ ‘iwadh), jika ditambah (adanya) pemindahan sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat orang yang diberi hibah (dimana pemberian itu) sebagai penghormatan (ikrâman) maka itu adalah hadiah. Jika ditambah bahwa pemindahan pemilikan itu ditujukan kepada orang yang membutuhkan, sebagai suatu taqarrub kepada Allah dan untuk meraih pahala akhirat maka itu adalah sedekah. Perbedaan hadiah dari hibah adalah dipindahkannya sesuatu yang dihibahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Karena itu, lafal hadiah tidak bisa digunakan dalam hal property. Dengan demikian, tidak dikatakan, “Saya menghadiahkan rumah atau tanah.” Akan tetapi, hadiah itu digunakan dalam hal harta bergerak yang bisa dipindah-pindahkan seperti pakaian, hamba sahaya, dsb. Walhasil, dari macam-macam itu bisa dibedakan antara yang umum dan yang khusus. Jadi semua hadiah dan sedekah merupakan hibah, tetapi tidak sebaliknya.
Ketentuan Tentang Hadiah
Hadiah sebagai bagian dari hibah kehendaknya bisa datang dari satu pihak saja, yaitu dari pihak pemberi hadiah. Namun, para fukaha tetap mengklasifikasikan hibah, termasuk di dalamnya hadiah, sebagai akad. Hal itu karena meski kehendaknya bisa dari satu pihak saja, namun jika penerima hibah atau penerima hadiah itu menolaknya maka hibah atau hadiah itu tidak sempurna.
Sebagai sebuah akad, hadiah memiliki tiga rukun. Pertama, adanya al-‘âqidân, yaitu pihak pemberi hadiah (al-muhdî) dan pihak yang diberi hadiah (al-muhdâ ilayh). Al-Muhdî haruslah orang yang layak melakukan tasharruf, pemilik harta yang dihadiahkan dan tidak dipaksa. Al-Muhdâ ilayh disyaratkan harus benar-benar ada saat akad. Ia tidak harus orang yang layak melakukan tasharruf saat akad hadiah itu. Jika al-muhdâ ilayh masih kecil atau gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali atau mushi-nya.
Kedua, adanya ijab dan qabul. Hanya saja, dalam hal ini tidak harus dalam bentuk redaksi (shighat) lafzhiyah. Hal itu karena pada masa Nabi saw., hadiah dikirimkan kepada Beliau dan Beliau menerimanya, juga Beliau mengirimkan hadiah tanpa redaksi lafzhiyah. Fakta seperti itu menjadi fakta umum pada masa itu dan setelahnya.
Akad hadiah merupakan al-‘aqd al-munjiz, yaitu tidak boleh berupa al-‘aqd al-mu’alaq (akad yang dikaitkan dengan suatu syarat) dan tidak boleh berupa al-‘aqd al-mudhâf (akad yang disandarkan pada waktu yang akan datang). Contoh al-‘aqd al-mu’alaq, jika seseorang berkata, “Saya menghadiahkan satu juta kepada Anda jika Anda pergi ke Bandung.” Akad hadiah ini tidak sah. Contoh al-‘aqd al-mudhâf, jika dikatakan, “Saya menghadiahkan sepeda ini kepada Anda mulai bulan depan.” Akad ini juga tidak sah. Sebagai al-‘aqd al-munjiz, implikasi akad hadiah itu langsung berlaku begitu sempurna akadnya dan terjadi al-qabdh. Artinya, al-muhdâ (hadiah) itu telah sah dimiliki oleh orang yang diberi hadiah.
Ketiga, harta yang dihadiahkan (al-muhdâ). Al-Muhdâ (barang yang dihadiahkan) disyaratkan harus jelas (ma‘lûm), harus milik al-muhdî (pemberi hadiah), halal diperjualbelikan dan berada di tangan al-muhdî atau bisa ia serah terimakan saat akad. Menurut Imam Syafii dan banyak ulama Syafiiyah, barang itu haruslah barang bergerak, yaitu harus bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal itu karena seperti itulah yang berlangsung pada masa Nabi saw, disamping tidak ada riwayat yang menjelaskan adanya hadiah berupa rumah, tanah, dsb itu pada masa Nabi saw. dan para Sahabat.
Di samping ketiga rukun itu ada syarat yang harus terpenuhi sehingga hadiah itu sempurna, yaitu harus ada al-qabdh (serah terima), yakni secara real harus ada penyerahan al-muhdâ kepada al-muhdâ ilayh. Jika tidak ada ijab qabul secara lafzhiyah maka adanya al-qabdh ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan pemilihan itu. Penyerahan harta itu dianggap merupakan ijab dan penerimaan hadiah oleh al-muhdâ ilayh merupakan qabulnya. Untuk barang yang standarnya dengan dihitung, ditakar atau ditimbang (al-ma’dûd wa al-makîl wa al-mawzûn) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahterimakan. Adapun harta selain al-ma’dûd wa al-makîl wa al-mawzûn seperti pakaian, hewan, kendaraan, barang elektronik, dsb maka yang penting ada penyerahan pemilikan atas barang itu kepada al-muhdâ ilayh dan qabdh-nya cukup dengan menggesernya atau jika hewan dengan melangkahkannya, atau semisalnya.
Hukum Memberi Hadiah
Memberi hadiah hukumnya sunnah. Abu Hurairah berkata, Nabi saw. bersabda:
تَهَادَوْا تَحَبُّوْا
Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian saling mencintai (HR al-Bukhari, al-Baihaqi dan Abu Ya‘la).5
Bahkan Nabi saw. mendorong untuk memberi hadiah meski nilainya secara nominal kecil:
يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ
Hai para Muslimah, janganlah seorang wanita merasa hina (memberi hadiah) kapada wanita tetangganya meski hanya tungkai (kuku) kambing. (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Ahmad).
Sebaliknya, Nabi saw. melarang untuk menolak hadiah:
اَجِيْبُوْا الدَّاعِيَ وَلاَ تَرُدُّوْا الْهَدِيَّةَ وَلاَ تَضْرِبُوْا الْمُسْلِمِيْنَ
Penuhilah (undangan) orang yang mengundang, jangan kalian tolak hadiah dan jangan kalian memukul kaum Muslim. (HR al-Bukhari Ahmad, Abu Ya‘la dan Ibn Abi Syaibah).
Jika seseorang diberi hadiah dan tidak ada halangan syar‘i untuk menerimanya maka hendaknya ia menerimanya. Jika seseorang menolak hadiah kepadanya maka hendaknya menjelaskan alasannya untuk menghilangkan perasaan buruk di hati si pemberi. Hal itu seperti riwayat Sha’b ibn Jatstsamah bahwa ia menghadiahkan seekor keledai liar kepada Nabi saw. saat Beliau berada di Abwa atau Wadan, tetapi Beliau menolaknya. Lalu Beliau menjelaskan alasan penolakannya. Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku tidak menolak hadiahmu kecuali karena aku sedang berihram.” (HR al-Bukhari).
Boleh menerima hadiah dari orang kafir, karena dalam Shahîh al-Bukhârî diriwayatkan Nabi saw. pernah menerima hadiah dari Heraklius, Muqauqis, Ukaidir Dumatul Jandal, dan Raja Ailah. Beliau pun menerima hadiah dari orang kafir lainnya. Begitu pula boleh memberi hadiah kepada orang kafir selama orang itu bukan kafir harbi fi‘l[an],6 atau selama hadiah itu tidak membuat orang kafir bertambah kuat atau menjadi berani menyerang kaum Muslim.
Jika seseorang mendapat hadiah dan ia memiliki kelapangan maka disunahkan untuk membalasnya. Jika tidak, setidaknya memuji dan mendoakan pemberi hadiah. Jabir ra. menuturkan bahwa Nabi saw. pernah bersabda:
مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ
Siapa yang diberi sesuatu lalu ia memiliki kelapangan harta, hendaklah ia membalasnya; jika ia tidak memiliki kelapangan harta, hendaknya ia memuji (mendoakan)-nya. (HR Abu Dawud, Tirmidzi, al-Baihaqi).
Dalam riwayat at-Tirmidzi dari Usamah bin Zaid, pujian (doa) yang paling baik untuk itu adalah dengan mengatakan, “Jazâkallâh khayr[an] (Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik).”
Sekalipun diperintahkan untuk menerima hadiah dan dilarang menolaknya, ada beberapa macam hadiah yang justru tidak boleh (haram) diterima, di antaranya: Pertama, hadiah kepada penguasa, pejabat atau pegawai negara. Abu Humaid as-Sa’idi menuturkan bahwa Nabi saw. pernah mengangkat seseorang dari Bani Azad yang bernama Ibn al-Utbiyah (Ibn al-Lutbiyah) sebagai amil pemungut zakat, lalu ia kembali dan mengatakan, “Ya Rasul, ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya.”
Nabi saw. lalu berpidato, “Tidak pantas seorang petugas yang kami utus lalu datang dan berkata, “Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan untuk saya.” Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya lalu memperhatikan apakah itu dihadiahkan kepadanya atau tidak. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah ia datang membawa pemberian itu, kecuali ia pasti datang pada Hari Kiamat kelak memanggul barang itu di pundaknya.” (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Dawud).
Hadis ini menunjukkan hadiah itu datang karena jabatan, kedudukan atau tugasnya.
Kedua, hadiah yang diberikan karena adanya akad al-qardh (utang). Anas ra. menuturkan, Nabi saw. pernah bersabda:
إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ يَقْبَلْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
Jika salah seorang di antara kalian mengutangi suatu utang lalu yang berutang memberinya hadiah atau membawanya di atas hewan tunggangan maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu, kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum utang-piutang itu. (HR Ibn Majah).
Ketiga, hadiah yang diberikan agar suatu kemungkaran dibiarkan atau agar penerima hadiah mengendurkan aktivitas amar makruf nahi mungkar atau yang semisalnya. Hadiah yang dimaksudkan untuk membatalkan yang hak dan mengokohkan yang batil, termasuk hadiah agar yang haq tidak disuarakan dan agar yang batil dibiarkan atau tidak dikritik, tidak boleh diterima. Apalagi hadiah yang diberikan agar kebatilan disuarakan dan disebarkan, atau agar kemungkaran diperintahkan, tentu lebih tidak boleh lagi diterima; termasuk di dalamnya hadiah dari negara atau lembaga asing untuk penyebaran ide selain Islam seperti demokrasi, HAM, pluralisme, liberalisme, dsb; atau hadiah agar ide-ide tidak islami seperti itu dibiarkan.
Masih ada beberapa macam hadiah yang tidak boleh diterima.7 Hal itu bisa kita lihat dalam penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Wallâh a‘lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]
Catatan kaki:
1 Al-Fayruz al-Abadi, al-Qâmus al-Muhîth, III/487; Ibn Sayidih, al-Mukhashish, III/67; Murtadha az-Zabidi, Tâj al-‘Urûs min Jawâhir al-Qâmûs, 1/8663; Ibn Manzhur, Lisân al-‘Arab, XIII/354.
2 Al-Qâmûs al-Fiqhî, 1/367, CD Maktabah Syamilah ishdar ats-tsaniy.
3 Mu’jam Lughah al-Fukahâ’, 1/493, CD Maktabah Syamilah ishdar ats-tsaniy.
4 An-Nawawi, Rawdhah ath-Thâlibîn wa ‘Umdah al-Muftîn, V/364-365, al-Maktab al-Islami, Beirut, cet. ii. 1405
5 Al-Bukhari, al-Adab al-Mufrad; al-Baihaqi, Syu’ab al-خmân, Abu Ya’la, Musnad Abiy Ya’lâ. Al-Hafizh Ibn Hajar berkata: isnadnya hasan.
6 Lihat QS. Mumtahanah [6]: 8-9
7 Tentang undian lihat al-Wa’ie no. 38.