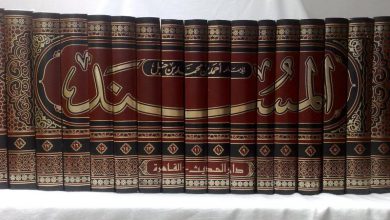Hadits
Tambang Milik Umum dan Milik Pribadi

قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: ابْنِ عَبْدِ الْمَدَانِ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ – قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ: الَّذِي بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ – فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ، قَالَ : فَانْتَزَعَ مِنْهُ
Ibnu al-Mutawakkil bin Abdi al-Madan berkata, dari Abyadh bin Hamal, bahwa dia pernah datang menemui Rasulullah saw. dan meminta diberi tambang garam—Ibnu al-Mutawakkil berkata—yang ada di Ma’rib. Lalu Rasul saw. memberikan tambang itu kepada Abyadh. Ketika Abyadh pergi, salah seorang laki-laki dari majelis berkata, “Apakah Anda tahu apa yang Anda berikan kepada dia? Tidak lain Anda memberi dia air yang terus mengalir.” Dia (Ibnu al-Mutawakkil) berkata: Lalu beliau menarik kembali tambang itu dari dia (Abyadh bin Hamal) (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Hibban, al-Baihaqi dan ath-Thabarani. Redaksi menurut Abu Dawud).
Imam at-Tirmidzi berkomentar, “Hadis Abyadh adalah hadis gharib.”
Ibnu Hibban meriwayatkan hadis ini di dalam Shahîh-nya. Syaikh Nashiruddin al-Albani menilai hadis ini hasan. Ibnu al-Qathan menilai hadis ini dha’if karena menurutnya selain Abyadh adalah majhul. Namun, Ibnu al-Mulaqin di dalam Badru al-Munîr mengatakan, “Tidak seperti yang dia (Ibnu al-Qathan) katakan. Saya telah menjelaskan hal itu di dalam takhrij saya untuk hadis-hadis Al-Wasîth. Karena itu rujuklah, nisacaya Anda akan mendapati apa yang menjelaskan jalur-jalurnya dan jawaban bagi orang yang menilainya cacat dan yang menetapkan ragam ungkapannya serta yang lain.”
Hadits ini dijadikan hujjah oleh para imam fuqaha seperti tercantum di dalam Al-Umm, Al-Mughni, Al-Majmû’, dsb. Sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Khathabi di dalam Ma’âlim as-Sunan, hadis yang demikian adalah hadis hasan.
Yang dimaksud ucapan Abyadh “istaqtha’a al-milha” adalah ma’din (mineral/barang tambang) garam. Dia meminta tambang itu agar diberikan kepada dirinya sehingga menjadi miliknya. Al-Ma’rib yang dimaksud adalah satu tempat di Yaman. Menurut Mula al-Qari di dalam Mirqât al-Mafâtîh Syarh Misykât al-Mashâbîh dan Abu Thayyib di dalam ‘Awn al-Ma’bûd, “Laki-laki yang mengatakan bahwa tambang itu seperti al-mâ`u al-‘iddu adalah al-Aqra’ bin Habis at-Tamimi. Ini seperti yang disebutkan oleh ath-Thayibi. Dikatakan bahwa dia adalah al-‘Abbas bin Mirdas.”
Dalam riwayat Ibnu Majah dan ath-Thabarani, laki-laki itu adalah al-Aqra’ bin Habis at-Tamimi.
Dalam hadis ini, semula Rasul saw memberikan tambang garam di Ma’rib itu kepada Abyadh bin Hamal. Namun, setelah diberitahu bahwa itu seperti al-mâ‘u al-‘iddu, maka Rasul saw. menarik kembali tambang garam itu. Ini menunjukkan bahwa tambang yang sifatnya seperti al-mâ‘u al-‘iddu tidak boleh diberikan kepada individu, yakni tidak boleh dikuasai dan dimiliki oleh individu. Hal itu memberikan pemahaman bahwa sifat seperti al-mâ‘u al-‘iddu itu menjadi sebab (‘illat) penarikan kembali pemberian itu.
Ibnu Zanjawaih, di dalam kitabnya, Al-Amwal mengatakan, “Pemberian beliau (Rasul saw.) kepada Abyadh bin Hamal, garam di Ma’rib, kemudian beliau tarik kembali dari dia, tidak lain beliau berikan kepada dia, dan itu dalam pandangan beliau adalah tanah mati yang dihidupkan dan dimakmurkan oleh Abyadh. Lalu ketika menjadi jelas bagi Nabi saw. bahwa itu al-‘iddu, yaitu yang zatnya tidak terputus, semisal mata air dan sumur, maka beliau menarik kembali tambang tersebut. Sebab Sunnah Nabi saw. dalam padang, api dan air, bahwa manusia semuanya berserikat padanya. Karena itu beliau tidak suka menjadikan barang-barang itu untuk dikuasai seseorang dengan menghalangi orang lain.”
Hadis Abyadh bin Hamal itu menunjukkan secara manthhuq bahwa tambang yang seperti al-mâ‘u al-‘iddu itu tidak boleh diberikan kepada individu, yakni tidak boleh dikuasai atau dimiliki oleh individu. Secara mafhum-nya hadis ini menunjukkan, jika tambang itu tidak seperti al-mâ‘u al-’iddu maka boleh diberikan kepada individu dan boleh dimiliki oleh individu. Rasul saw. pun pernah memberikan tambang al-Qabaliyah kepada Bilal bin Harits al-Muzani dan beliau menuliskan dokumen pemberian itu. Dari riwayat Ibnu Zanjawaih di dalam Al-Amwâl halaman 742 hadis nomor 1267, terkait penjualan tanah itu oleh keturunan Bilal kepada Umar bin Abdul Aziz, tambang al-Qabaliyah itu termasuk bahan tambang di dalam tanah yang untuk mengeluarkannya perlu biaya.
Jadi status kepemilikan tambang dikaitkan dengan sifat al-mâ‘u al-‘iddu. Sifat ini bisa dipahami menjadi ‘illat ketidakbolehan suatu tambang dimiliki oleh individu. Adapun makna al-mâ‘u al-‘iddu, di al-Qâmûs al-Muhîth maknanya adalah air yang memiliki deposit yang tidak terputus seperti mata air. Makna ini yang dikuatkan oleh al-Azhari.
Menurut al-Asma’iy, al-mâ‘u al-‘iddu, yakni yang terus-menerus yang tidak terputus. Itu semisal air mata air dan air sumur. Menurut Al-Hafizh as-Suyuthi di dalam Qût al-Mughtadzâ ‘alâ Jâmi’ at-Tirmidzî dan Abu Thayyib al-Abadi di dalam ‘Awn al-Ma’bûd, al-mâ‘u al-‘iddu adalah yang zatnya terus-menerus tidak terputus. Menurut Ibnu al-Atsir di dalam Jâmi’ al-Ushûl, al-mâ‘u al-‘iddu adalah air yang mengalir terus yang zatnya tidak terputus karena banyak dan melimpah.
Dengan demikian tambang yang depositnya besar, berdasarkan hadis Abyadh bin Hamal itu, tidak boleh diserahkan dan tidak boleh dimiliki oleh individu. Penyamaannya dengan al-mâ‘u al-‘iddu, yang itu disetujui dan dibenarkan oleh Rasul saw. dan menjadi sebab penarikan beliau atas pemberiannya kepada Abyadh, juga mengisyaratkan bahwa status kepemilikannya seperti air yang terus mengalir yakni seperti halnya mata air. Artinya, sama seperti mata air yang terus mengalir, status tambang yang depositnya besar itu adalah milik umum, yakni semua rakyat berserikat di dalamnya.
Jadi yang menjadi penentu adalah jumlah deposit bahan tambang itu, tanpa membedakan jenisnya, apakah bahan tambang permukaan yang untuk mengambilnya tidak memerlukan alat dan biaya; ataukah bahan tambang di dalam tanah yang untuk mengambilnya perlu alat, biaya dan keahlian. Selanjutnya, negaralah (imam atau khalifah) yang menentukan batasan jumlah deposit suatu bahan tambang yang sudah dinilai memenuhi sifat al-mâ‘u al-‘iddu, yang karenanya tidak boleh dimiliki oleh inidvidu atau swasta; melainkan statusnya adalah milik umum seluruh rakyat.
WalLâh a’lam. [Yahya Abdurrahman]